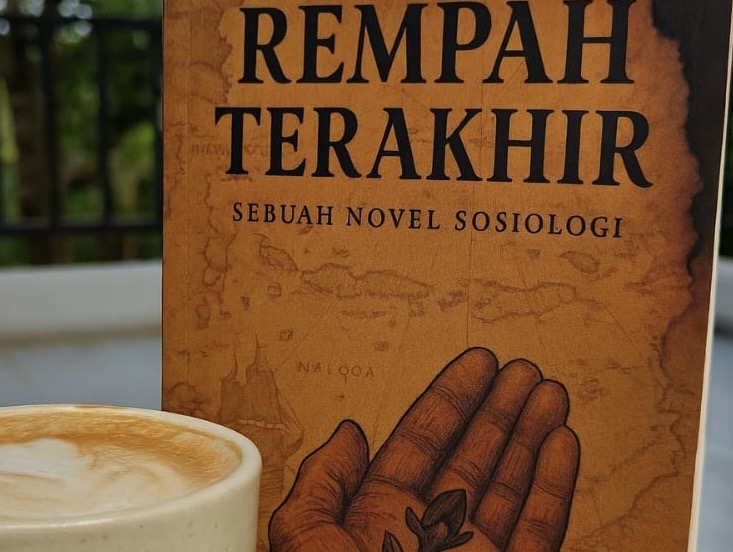Refleksi Sosiologis dan Sastra atas Rempah Terakhir karya Herman Oesman
Rahmat Abd Fatah Dosen Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Ternate, 17 Oktober 2025
Ada sesuatu yang sunyi namun tajam ketika membaca Rempah Terakhir Herman Oesman. Kolega kami di Fisip Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Seorang sosiolog senior yang konsisten menenun realitas sosial, seorang “Profesor” makna, walau secara administratif belum disandangnya, kedalaman keilmuan seturut karakter kritis-reflektifnya membuat kadang abai pada sesuatu yang sifatnya formal-administratif.
Herman tidak menulis sekadar kisah, melainkan membuka ruang batin bagi pembaca untuk mendengar suara yang kerap diabaikan. Suara tanah, suara manusia yang hidup darinya, dan suara waktu yang menua di antara keduanya. Buku ini, diterbitkan pada Oktober 2025 oleh Tanah Air Beta Yogyakarta bekerja sama dengan UMMU Press.
Membaca Rempah terakhir terasa seperti perjalanan ziarah menuju tanah kelahiran yang terluka namun tetap bernapas. Dalam 115 halaman yang padat dan berisih, Herman menenun sosiologi dan sastra menjadi satu tubuh narasi yang hidup, merangkul para petani cengkih, nelayan, dan mereka yang menatap langit Maluku Utara dengan sabar dan setia.
Pulau Tefa yang menjadi latar cerita bukan sekadar tempat, melainkan tokoh utama yang memiliki ingatan dan perasaan. Di dalamnya, dunia bergerak cepat. Kebun berubah menjadi tambang, hutan menjadi peta konsesi, dan langit yang dulu beraroma cengkih kini diselimuti kabut logam. Namun Herman tidak mengajak pembacanya untuk berduka tanpa arah, ia mengajak untuk memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari kesadaran.
Ia menulis dengan kesadaran seorang sosiolog, yang melihat struktur masyarakat bekerja dalam senyap, tetapi ia juga menulis dengan hati seorang penyair yang mendengarkan bisikan angin di sela daun pala.
Novel ini hidup dari tokoh-tokohnya yang sederhana tapi berjiwa besar. Ada Rafi, yang dulu bermimpi memetik cengkih bersama ayahnya namun akhirnya menggali tanah demi tambang. Ada Amira, yang menulis peta dan menjaga hutan terakhir di pulau itu seperti menjaga ingatan ibunya. Ada Sahla, seorang periset yang bertanya dengan tanah dan menolak menyerah pada logika modernitas. Ada Nina, jurnalis muda yang datang dari kota, membawa rasa ingin tahu dan pulang dengan luka yang berubah menjadi kesadaran. Melalui mereka, Herman memperlihatkan wajah masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan oleh proyek pembangunan.
Bahasa Herman mengalir perlahan seperti sungai yang membawa cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalimatnya lembut tapi berdaya, seperti seseorang yang berbicara bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengingatkan. Ia menulis agar pembaca berhenti sejenak, menatap kebun yang gersang, lalu menyadari bahwa tanah bukan hanya benda yang bisa dijual, tetapi bagian dari kehidupan yang memberi napas. Inilah kekuatan Rempah Terakhir: kesederhanaannya menembus kesadaran.
Ketika dunia berubah dan tambang datang membawa janji kemakmuran, Pulau Tefa menjadi simbol dari banyak tempat di Maluku Utara. Di sini, sosiologi bertemu dengan sastra. Herman tidak menggambarkan konflik secara hitam putih, melainkan melalui lapisan-lapisan sosial yang saling berkelindan. Ia memperlihatkan bagaimana masyarakat yang hidup dari rempah yang dulu menjadi jantung ekonomi dunia, kini harus berhadapan dengan realitas baru yang menuntut mereka menjual sumber daya yang tersisa. Namun dalam kehilangan itu, ada kekuatan yang tumbuh yaitu kekuatan mengingat.
Bab-bab terakhir buku ini menandai titik balik. Bahwa Pulau yang Tak Sepenuhnya Tenggelam, Setelah Langit Dibuka, hingga epilog Tanah yang Mengingat. Semua menandai kembalinya harapan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan keheningan. Langit yang lama tertutup debu akhirnya cerah kembali. Warga tidak merayakannya dengan pesta, melainkan dengan doa tanpa suara. Mereka tahu bahwa perubahan tidak selalu datang dari luar, melainkan tumbuh perlahan dari dalam hati yang tak menyerah. Amira duduk di tepi kebun kecil, membaca catatan ibunya, sementara anak-anak menanam pohon cengkih baru. Di tangan mereka, ingatan menemukan bentuk baru.
Rempah Terakhir bukan cerita tentang perang, melainkan tentang keberanian menjaga yang tersisa. Herman menulis dengan empati yang jernih. Ia tahu, perjuangan terbesar manusia bukan melawan kekuasaan, melainkan melawan lupa. Dalam sosiologi lingkungan, ingatan adalah bentuk perlawanan. Dalam sastra, ia adalah doa. Buku ini menjembatani keduanya. Ia mengajarkan bahwa manusia dan tanah saling menghidupi, dan ketika salah satunya terluka, yang lain ikut berdarah.
Membaca karya ini seperti berjalan menyusuri jalan setapak di kebun tua setelah hujan. Ada bau tanah basah, ada kenangan yang muncul tanpa dipanggil. Di antara halamannya, kita mendengar suara yang akrab yaitu suara para petani yang menunggu musim, para nelayan yang memandang laut, para ibu yang menumbuk pala di beranda rumah bambu. Semua hadir tanpa slogan, tanpa amarah, hanya dengan kesetiaan pada hidup yang sederhana.
Novel ini menutup dirinya dengan cara yang tidak heroik, tetapi manusiawi. Pulau Tefa tidak kembali seperti semula, namun ia mengingat. Ia menolak tenggelam dalam peta digital yang dingin. Ia tetap hidup dalam doa orang-orang yang percaya bahwa tanah, betapapun lelahnya, akan selalu memanggil pulang mereka yang mencintainya.
Rempah Terakhir adalah saksi bisu dari zaman yang bergegas, sekaligus pengingat bahwa masih ada ruang untuk menanam, mencium aroma rempah, dan menyebut nama pulau dengan lembut. Dalam buku ini, Herman Oesman telah menulis bukan hanya sebuah novel sosiologi, melainkan sebuah kesaksian tentang manusia yang tak ingin melupakan dari mana mereka berasal, dan tentang tanah yang meski terluka, masih berani mencintai manusia yang menginjaknya.